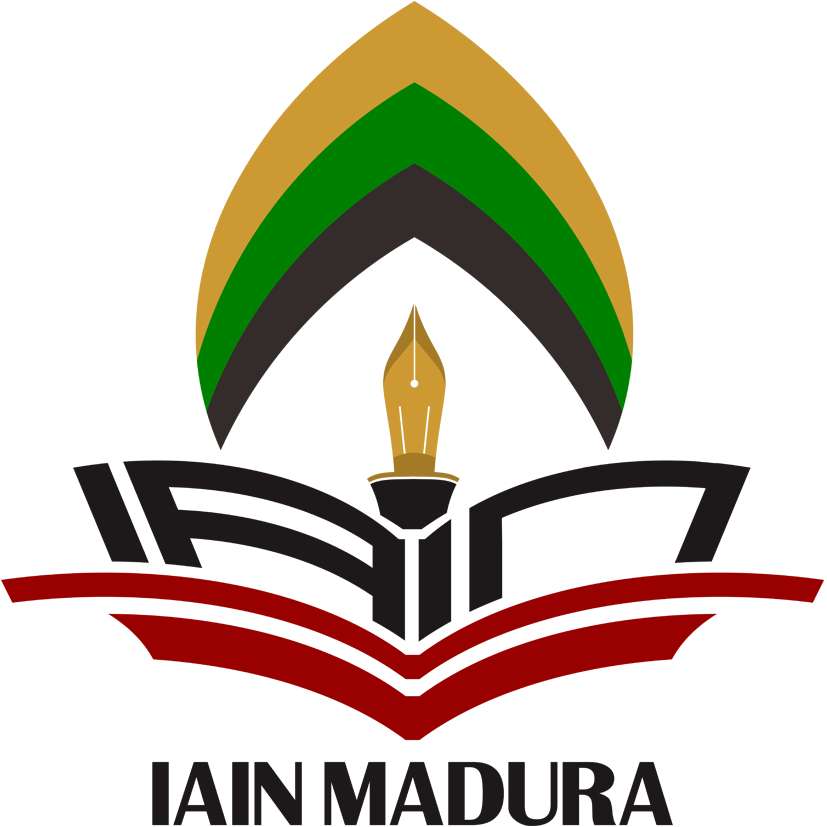MADUROLOGI: Epistema Madura Menuju Kedewasaan Berbangsa
- Diposting Oleh Admin Web LP2M
- Sabtu, 2 Maret 2024
- Dilihat 918 Kali
Abstrak:
Takdir sebuah rumah yang tidak mampu lagi memberikan perlindungan warganya adalah keruntuhan. Perubahan adalah sunnatullah; persoalannya adalah perubahan dapat membawa seseorang kemanapun dan untuk untuk itu meniscayakan kepunahan eksistensialnya: suatu kondisi yang menjadikan seseorang terasing dari titik berangkatnya (al-mabda’) dan kehilangan orientasinya (al-ghoyah). Dalam situasi keterasingan ini seseorang rentan untuk terserap kepada apapun dan tertambat di manapun hingga menjadikan dirinya hanya sebagai bayang-bayang, menjadi remeh, seseorang tanpa identitas dan harga diri (‘irdlun). Sesungguhnya perubahan jenis ini merupakan perubahan seseorang atau kelompok tanpa kekuatan tawar sehingga yang terjadi adalah deviasi atau bahkan negasi diri dan bukan suatu dinamika transformatif dirinya dengan tetap berpijak pada khazanah pengetahuan dan tradisinya dalam merespon tantangan dan sekaligus kebutuhan eksistensialnya. Pada titik inilah sebuah otentisitas menjadi taruhan. Madura telah dan sedang bergelut dengan takdir eksistensialnya di tengah-tengah kekuatan pengubah dunia yang bernama modernisme dengan piranti teknologi informasi yang sangat dominan dan hegemonik. Tentu saja otentisitas Madura dan kemaduraan tidak harus berarti penolakan terhadap teknologi karena hal itu bukan saja konyol tetapi juga mustahil. Apa yang harus dilakukan adalah mengkritisi struktur pengetahuan di balik modernisme Barat (atau struktur pengetahuan dan tradisi lainnya) melalui khazanah struktur pengetahuan dan tradisinya sendiri dan pada saat yang sama Madura musti berani melakukan kritik diri dari dalam dirinya sendiri (bukan seperti yang terjadi selama ini: kritik diri tetapi dengan menggunakan struktur pengetahuan orang lain). Inilah makna dialog, kedua jenis pengetahuan (dan juga tradisi ) sama-sama dipahami dan didudukkan secara adil karena disorot dari dalam dirinya sendiri. Dengan cara ini, otentisitas kedua struktur pengetahuan (dan tradisi) dikenali keunikannnya masing-masing; sehingga dialog tersebut dapat mengahasilkan transformasi budaya dan kedirian yang tetap dapat mengenali otentisitasnya dan bukannya perubahan yang lebih merupakan bentuk pengingkaran diri ,deviasi atau bahkan negasi.
Pendahuluan
Persoalan besar bangsa Indonesia adalah pencarian identitas keIndonesiaan dan pemaknaan konsep kewarganegaraan. Kedua hal ini wajar menjadi sumber dinamika dan sekaligus sumber pertikaian bangsa karena kedua persoalan tersebut merupakan fenomena baru yang eksistensinya masih lebih merupakan cita-cita dari para pendiri bangsa ini. Kelahiran Indonesia sebagai entitas negara dan bangsa yang “hanya”[1] berbekal semangat yang mewujud pada konsep besar NKRI. Adapun wujud kongkritnya, paling tidak dari bukti kesejarahan, budaya dan politis, masih selalu dalam proses pencarian, bahkan sampai saat ini. Pertanyaaan besar yang selalu muncul adalah, apa wujud ke Indonesiaan dan apa arti menjadi Indonesia? Sungguh yang benar-benar eksis dalam pengertian sosio-kultural dan politis adalah realitas Nusantara. Tetapi realitas Nusantara ini bukanlah suatu entitas politis-kultural yang tunggal. Ia merupakan mosaik berbagai suku-bangsa dengan peragaan budaya, agama, dan politik yang beragam dan independent. Sehingga problem nyata bangsa ini adalah mencari model hubungan yang adil dan wajar antara entitas kedaerahan dan pusat dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, terkait dengan cinta segi tiga dari tema ini, hubungan Islam dan kebangsaan tidak akan tuntas sebelum hubungannya dengan budaya lokal/kedaerahan tuntas sebab kenyataaan menunjukkan realitas Nusantara yang eksis terlebih dulu sebelum kelahiran rumah besar Indonesia, Islam merupakan unsur dominan pembentuk masing-masing lokalitas Nusantara terutama di sebagian besar Sumatra, Jawa, Kalimantan,Sulawesi, Maluku, dan kepulauan lainnya. Artinya seorang Muslim harus menjawab dulu apa makna Islam bagi dirinya di satu sisi, dan apa pula makna sosio-kultural masyarakatnya baginya sebelum dia dapat menjawab persoalan makna menjadi manusia Indonesia.
Think Spiritually; Act Culturally
Menjadi Muslim berarti kesadaran untuk mematuhi semua ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-quran dan As-sunnah. Untuk pernyataan ini , penulis yakin semua Muslim sepakat. Persoalan muncul ketika seseorang menyadari dirinya sebagai Muslim di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan sekaligus sebagai warga masyarakat dan bangsa. Sebagai warga masyarakat yang mendiami lokalitas tertentu dengan identitas etnis dan budaya tertentu, seorang Muslim senyatanya selalu melakukan dialog diri antara keimanannya akan nilai-nilai agamanya dengan realitas sosio-kultural masyarakatnya. Dengan `demikian, praksis keagamaan seseorang sesungguhnya selalu merefleksikan suatu peragaan kulturalnya. Inilah dasar mengapa studi tentang kebudayaan, selalu berarti kesiapan untuk terbuka terhadap nilai-nilai spiritualitas agama karena kebudayaan --dalam lapisan terdalamnya-- selalu menjadi lokus bagi peragaan spiritualitas seseorang bersama-sama komunitasnya. Demikian juga dalam setiap studi tentang agama, seseorang harus terbuka terhadap dimensi kultural yang mengiringi semua praksis keagamaan.
Dalam dialog agama-kebudayaan yang niscaya terjadi pada setiap individu, --persoalan krusial yang harus disadari-- adalah bahwa nilai-nilai dasar agama yang mewujud pada keimanan adalah sesuatu yang telah sempurna, dalam arti seseorang dengan kesadaran dirinya telah menyerahkan sendiri kepercayaannya kepada agama tersebut. Sementara budaya selalu dinamis, sebab jika tidak, maka ia akan menjadi beku di tengah-tengah dinamika masyarakatnya. Hakekat keimanan agama adalah paripurna dan transenden, sementara realitas budaya selalu relatif dan imanen. Inilah problem autentisitas manusia beragama dan sekaligus berbudaya.
Sebagai sebuah nilai dasar yang melampaui zaman dan tempat, pemaknaan ajaran agama jelas memerlukan kecerdasan dan kedewasaan dari penganutnya yang juga merupakan manusia berbudaya. Kedewasaan tersebut termaktub dalam paradigma : “Praksis keagamaan adalah bukan hakekat agama itu sendiri. Ia lebih merupakan tindakan manusia berbudaya yang beragama”. Mengabaikan paradigma ini akan berujung pada kezaliman terhadap agama dan budaya itu sendiri. Seringkali seseorang memutlakkan yang relative, dan merelatifkan yang mutlak.[2] Contoh yang menggambarkan persolan ini adalah masalah shalat dengan “sarung –baju takwa-kopiah vs odeng-pesa’-gombor” (Contoh ini dapat diaplikasikan ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas lagi semisal Islam vs Partai Politik; )[3]
Madurologi Sebagai Suatu Jawaban
Madurologi dapat dipahami sebagai menempatkan Madura sebagai objek kajian. Dalam pengertian ini Madura dapat didekati dengan berbagai konsep yang berkembang pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Tetapi Madurologi juga dapat dipandang sebagai suatu disiplin yang menuntun setiap kajian tentang Madura. Ia adalah paradigma yang di-derivasi dari labenswelth manusia Madura.[4] Dengan demikian Madurologi merupakan pampatan merasa, berpikir, berperilaku dan juga kedirian Madura seperti yang tergelar pada budayanya. Dengan kata lain Madurologi adalah abstraksi konseptual Madura dengan keseluruhan jagad Madura yang terhayati oleh Manusia Madura. Konseptualisasi ini dilakukan dengan berjangkar pada qualitatif research yang mengedepankan perspektif dari dalam dan menggali jaringan makna yang terpateri dalam simbol-simbol budaya. Dengan demikian Madurologi adalah konstruksi jagad Madura melalui perspektif dalam sebagaimana yang terhayati masyarakatnya. Dalam pengertian kedua inilah Madurologi akan dirancang di lingkungan STAIN Pamekasan.
Dengan bingkai pikir semacam ini, Madurologi menuntut penggalian khazanah Madura dengan menyentuh buminya melalui grounded research dan kejelian serta kesabaran akan detail etnografi. Mungkin langkah ini terasa berat bagi sebagian orang yang terbiasa surfing informasi kepustakaan untuk berpuas diri dengan konstruk orang lain dan berhenti pada perspektif liyan.. Kerja etnografis deskriptif harus dilakukan untuk memperoleh raw material yang memadai bagi upaya membangun landasan Rumah Madurologi.[5]
Ketika data-data lapangan tersebut telah tersedia, kerja sesungguhnya bagi embrio Madurologi barulah dimulai yang meliputi kerja analisis, teorisasi dan berujung pada grand concept. Dari grand concept inilah dilakukan penjelajahan nalar untuk menemukan diri otentik madura. Pada tingkatan ini sang Madurolog senyatanya tengah menyumbang khazanah kemanusiaan dan di atas niatan mulia inilah Madurologi dilahirkan.[6] Ia tidak berangkat dari prejudice ras ataupun agama yang akan berujung pada klaim superioritas chauvinistik sebab jika ini yang menyeruak maka sebaiknya janin itu tidak perlu lahir karena hanya akan menambah daftar panjang kebodohan manusia.
Madurologi, sebagai sejenis human progress, masih merupakan obsesi.Tetapi impian ini bukan tidak mungkin diwujudkan jika kita para akademisi berani memeluk bumi Madura dengan keseluruhan cinta. Kedepan, penelitian yang berbasis grounded harus menjadi prioritas jika kita benar-benar menginginkan Rumah Madurologi dapat tegak berdiri di tengah–tengah belantara konstruk realitas lainya dalam keharmonian bermartabat. Pada titik inilah semua stigma dan stereotype madura akan hilang dengan sendirinya. Fa ‘ala hadihi al-niyat, Madurologi didirikan untuk memeluk dan memaknai dinamika jagad Madura yang sampai saat ini masih terasa kuat aroma konstruk liyan meskipun juga terasa adanya upaya untuk menjadi diri sendiri.
Jagad Madura senyatanya merupakan pampatan akulturatif kearifan Madura dalam interaksinya yang panjang dengan Islam. Pesantren Jan Tampes, yang oleh Mastuhu disebut sebagai pesantren tertua di Madura dan kemungkinan, paling tidak, seusia dengan pesantren Ampel Denta, meskipun masih bersifat asumtif, dan juga Pasean, sebuah desa kuno di pantura Madura yang berdasarkan pakem Chippery (ilmu tentang makna tempat) sebuah ilmu bantu sejarah, menegaskan bahwa hubungan Madura dengan pusat-pusat Islam Nusantara telah terjadi sejak masa yang lama. Dalam interaksi yang panjang ini, Madura telah begitu lekat menyerap dan diserap ke dalam nilai-nilai keIslaman sehingga budaya keberIslaman yang terbentuk melebihi tingkatan akulturatif. Dalam akulturasi kedua unsur budaya masih dapat dibedakan satu dari lainnya. Tidak demikian halnya dengan budaya Madura, di mana sulit dibedakan mana unsur lokal dan mana unsur Islam semisal dalam hierakhi ketaatan Madura yang terumuskan dalam prinsip BuPa’ Babu’ Guru Ratoh. Di sini tidak terlihat lagi mana unsur lokal dan mana unsur Islam. Sehingga yang terjadi lebih dekat pada fusi budaya dan bukan sekadar penjajaran dua unsur. Pada tataran ini pula dapat dibenarkan terjadinya identifikasi etnis ke dalam identifikasi agama sehingga dapat dinyatakan “Madura adalah Islam dan atau Islam adalah Madura, sebagimana identifikasi serupa terjadi pada masyarakat Melayu (Sumatera dan Malaysia), , Pattani (Thailand Selatan), Hui (di Cina), atau Moro di Mindanau (Filipina). Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa Madurologi, ketika telah mampu menggali dan membangun epistemanya sendiri, dapat dijadikan sebagai contoh dari salah satu model keberIslaman Nusantara.
Tentu saja dalam membangun epistema Madura (Madurologi) ini harus tetap disadari dinamika yang terjadi pada budaya Madura. Tetapi meskipun realitas budaya itu niscaya cair dan dinamis, bukan berarti sebuah budaya tidak dapat dikaji secara ajeg dengan menyandarkan adanya dua aspek dalam budaya yaitu aspek sistem nilai (sisi kebudayaan) yang dianut pada masyarakat pemilik budaya tersebut; dan aspek perwujudannya yang bersifat material-konkrit (sisi peradabannya).[7] Bukti-bukti empirik menunjukkan perubahan yang cepat itu hanya terjadi pada tataran peradabannya (wujud materialnya) sementara sistem nilainya tetap berlangsung dan sulit mengalami perubahan. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa arsitektur asli Madura yang berwujud tanian lanjheng saat ini sudah bisa dikatakan punah, tetapi nilai-nilai kekerabatan tradisionalnya yang mendasari arsitektur tanian lanjheng tersebut masih melekat kuat. Tentu saja dengan beberapa penyesuaian perwujudan dan pengungkapannya. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa ranah sistem nilai sebuah budaya dapat tetap hidup meskipun pengungkapan materialnya mengalami perubahan dengan cepat.
Dengan demikian epistema Madura (Madurologi) tersebut akan dibangun dengan menggali lebih dalam sistem nilai Madura dan pemaknaannya yang diyakini, berdasar bukti-bukti empirik , masih tetap kokoh dianut oleh masyarakat Madura meskipun wujud material dari sistem nilai tersebut telah berubah. Dalam proses penggalian dan penyusunan epistema Madura ini menjadi tidak relevan lagi untuk mempertentangkan secara polaristik antara Islam dengan Madura karena bukti-bukti sejarah dan antropologis menegaskan bahwa Islam telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kemaduraan itu sendiri. Tetapi harus tetap disadari bahwa: pertama, pemaknaan nilai-nilai Islam itu berlangsung dalam bingkai budaya Madura dan, kedua proses dialog antara Islam dan budaya Madura tersebut tetap berlansung selamanya. Pada tataran inilah terlihat kebenaran pernyataan bahwa di balik setiap budaya selalu ada kearifan sebagai bentuk kecerdasan sebuah masyarakat mememnuhi hajat hidupnya secara material maupun ruhaniahnya. Dan pada titik ini pula terlihat arti penting kritik budaya. Madurologi hanya dapat tegak berdiri ketika masyarakat Madura menyadari bahwa dalam proses dialog tersebut meniscayakan kritik-diri sebagai prasyarat yang menjamin kedirian Madura tetap eksis. Dan berdasar pada bukti-bukti empiris, harus diyakini senyatanya kritik tersebut lebih banyak bersentuhan dengan sisi material budaya bukan pada sistem nilai yang mendasarinya.
Masih banyak relung-relung dalam budaya Madura yang menunggu untuk dirumuskan menjadi sebuah epistema Madura (Madurologi) yang digadang-gadang menjadi pijakan masyarakatnya menjalanii dan menjawab tantangan zamannya tanpa harus kehilangan pancer hidupnya. Kelahiran dan perumusan epistema Madura diharapkan memperkaya khazanah keIslaman Nusantara karena epistema Madura adalah tajalli nilai-nilai Islam dalam bingkai budaya Madura itu sendiri.
Penutup
Untuk mencapai tujuan epistema Madura “MADUROLOGI” tersebut maka langkah-langkah yang harus ditempuh meliputi tiga tahapan : pertama Penggalian data semua aspek budaya Madura dengan menggunakan model penelitian etnografis sebagai raw material bagi pemahaman kemaduraan. Kedua Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, dilakukan penafsiran dan pemaknaan terhadapnya dengan menggunakan prinsip-prinsip epistemologis untuk membangun epistema Madura (Madrologi). dan Ketiga Menyusun sisi aksiologis berdasar pada epistema Madura untuk membangun masa depan Madura yang lebih bermartabat; dan tahapan tahapan ini akan berlangsung secara dialektis seterusnya. Wa AllÄh a’lam bi al-sawÄb ( Disarikan dari Proseding Membangun Madura by Masyhur Abadi dan Erie Hariyanto)